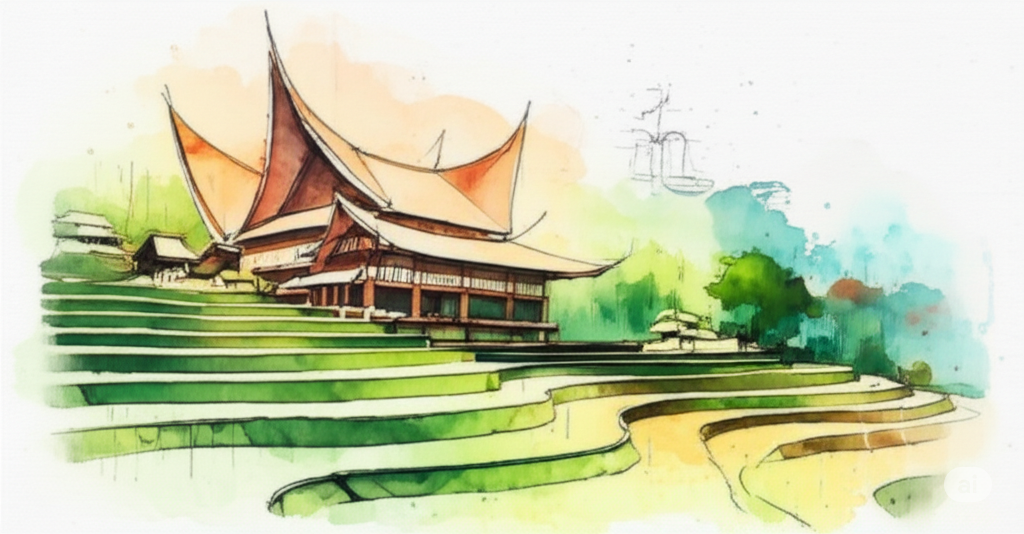Krisis Tanah Ulayat di Sumatera Barat: Pertarungan Hukum Adat dan Negara
Sebuah krisis tengah melanda Sumatera Barat, di mana dilaporkan sebanyak 324 dari 543 nagari induk telah kehilangan tanah ulayat mereka. Fenomena ini bukan sekadar masalah administrasi pertanahan, melainkan sebuah pertarungan fundamental antara sistem hukum adat yang telah mengakar kuat dengan hukum agraria modern yang berlaku di Indonesia. Keprihatinan mendalam melanda masyarakat adat seiring dengan terungkapnya akar permasalahan yang kompleks ini.
Ketiadaan Dokumen Hukum yang Sah dan Dominasi HGU
Menurut Prof. Kurnia Warman, seorang ahli hukum agraria, penyebab utama hilangnya tanah ulayat adalah ketiadaan dokumen hukum yang sah. Banyak tanah ulayat yang terlepas kepada investor melalui mekanisme Hak Guna Usaha (HGU) tanpa adanya sertifikat resmi yang melindungi kepemilikan adat. Ironisnya, ketika masa HGU berakhir, tanah-tanah yang tidak memiliki sertifikat ini secara otomatis beralih status menjadi tanah negara.
Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Forum Minang Maimbau (FMM) di Universitas YARSI, Kepala Kanwil BPN Sumbar, Teddi Guspriadi, menegaskan bahwa sertifikat adalah satu-satunya bukti legalitas tanah yang diakui oleh negara. Pernyataan ini menggarisbawahi kerentanan tanah ulayat yang selama ini hanya mengandalkan batas-batas tradisional atau patok tanpa adanya peta dan pengakuan resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Perdebatan Logika Hukum: Hukum Adat Versus Hukum Agraria
Menanggapi isu krusial ini, ET Hadi Saputra menawarkan perspektif yang berbeda dan cenderung kritis terhadap pendekatan hukum negara. Ia berpendapat bahwa terjadi “kesalahan logika hukum” dalam penanganan tanah ulayat. Menurutnya, tanah adat seharusnya tunduk sepenuhnya pada hukum adat, dan bukan pada hukum agraria yang dianggap sebagai warisan penjajah. Hadi Saputra merujuk pada Pasal 18b Ayat (2) UUD 1945, yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah ulayat, sepanjang adat tersebut masih hidup dan diakui dalam masyarakatnya.
Pandangan ini memicu perdebatan mendasar mengenai validitas dan efektivitas mekanisme sertifikasi ala hukum negara sebagai satu-satunya cara melindungi tanah ulayat. Apakah pengakuan terhadap eksistensi hukum adat itu sendiri tidak cukup memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi tanah-tanah tersebut? Inilah inti dari pertarungan hukum yang sedang berlangsung.
Urgensi Kehadiran Ahli Hukum Adat yang Kompeten
Lebih lanjut, ET Hadi Saputra menekankan betapa krusialnya bagi Minangkabau untuk memiliki ahli hukum adat yang kredibel dan kompeten. Ia menyerukan kepada universitas-universitas di Sumatera Barat untuk mulai fokus dalam menghasilkan lulusan hukum yang memiliki pemahaman mendalam dan keahlian dalam hukum adat. Keberadaan para ahli ini diharapkan mampu menjembatani jurang pemahaman antara hukum adat dan hukum negara, serta merumuskan strategi hukum yang lebih efektif dalam melindungi tanah ulayat dari potensi kehilangan.
Harapan dari Keberhasilan Sertifikasi di Tingkat Nagari
Di tengah perdebatan hukum yang kompleks, terdapat secercah harapan dari beberapa nagari yang telah berhasil melindungi tanah ulayat mereka melalui proses sertifikasi. Nagari Tabek Patah dan Sungayang menjadi contoh nyata keberhasilan dalam mendaftarkan tanah ulayat mereka ke BPN. Keberhasilan ini membuktikan bahwa proses pendataan dan sertifikasi, jika dilakukan dengan pemahaman dan mengakomodasi kearifan lokal, dapat menjadi solusi konkret dalam mengamankan aset berharga masyarakat adat.
Menuju Solusi Komprehensif
Isu hilangnya tanah ulayat di Sumatera Barat adalah permasalahan multidimensi yang memerlukan pendekatan holistik. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), para pakar hukum (baik hukum agraria maupun hukum adat), serta partisipasi aktif dari masyarakat adat itu sendiri. Perlindungan yang efektif terhadap tanah ulayat hanya akan terwujud melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum adat, implementasi hukum agraria yang mampu mengakomodasi kearifan lokal, serta pendampingan dari para ahli hukum adat yang kompeten dan berdedikasi. Masa depan tanah ulayat dan keberlanjutan identitas budaya Minangkabau sangat bergantung pada kemampuan kita untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.