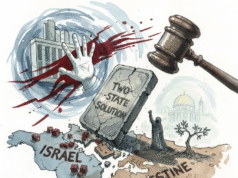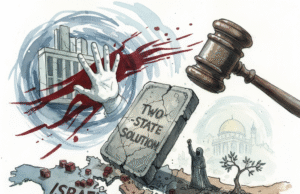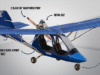Tahun Rilis: 2025 (Premiere Rotterdam 2 Februari 2025, Rilis Indonesia 5 Juni 2025)
Durasi: 130 Menit (tersedia versi 17+ dan 21+ uncut)
Penulis Naskah: Hanung Bramantyo, Z.Z. Mulja Galih
Sutradara: Hanung Bramantyo
Genre: Drama (dengan elemen thriller, budaya, dan seksualitas)
Rumah Produksi: MVP Pictures, Dapur Films
Film Gowok: Kamasutra Jawa (2025), garapan Hanung Bramantyo, datang dengan gembar-gembor luar biasa. Mengangkat tradisi “gowok”—perempuan yang mendidik calon pengantin pria tentang seksualitas dan tubuh perempuan—film ini janji mau menggali isu sensitif yang selama ini tabu: pendidikan seks dalam budaya Jawa, dekonstruksi patriarki, hingga pemberdayaan perempuan. Sebuah niat yang sangat mulia, katanya, di tengah lautan film horor dadakan dan komedi yang cuma bisa bikin dahi berkerut. Tapi, di balik semua klaim “edukasi seks tanpa jorok” dan “penghormatan budaya” itu, kok ya film ini malah terasa seperti etalase provokasi yang dibungkus rapi dengan kain batik, bikin kita bertanya-tanya, “Ini beneran mau ngedukasi atau cuma cari sensasi biar laku? Jangan-jangan, pulang dari bioskop, kita cuma dapat ide-ide baru, tapi bukan yang bersifat edukasi.”
Visual yang ‘Berani’, tapi Pesan ‘Malas’
Dari segi artistik, Gowok lumayan menjanjikan. Sinematografi Satria Kurnianto katanya berhasil mengemas adegan intim secara puitis, menghindari kesan vulgar, dan lebih fokus pada emosi. Akting jajaran pemainnya, yang bertabur nama besar seperti Raihaanun, Lola Amaria, Reza Rahadian, Devano Danendra, hingga Slamet Rahardjo, tentu saja diharapkan bisa menghidupkan karakter-karakter kompleks ini. Penggunaan bahasa Jawa ngapak dan detail budaya seperti cenil dan blangkon juga patut diacungi jempol karena berusaha menguatkan nuansa lokal. Mungkin para pembuat film berpikir, kalau sudah ada adegan “berani” tapi dibilang “artistik”, dan pakai bahasa Jawa, otomatis filmnya jadi maha karya. Niatnya bagus, biar enggak dicap film esek-esek murahan, padahal ya…
Tapi sayangnya, di balik klaim “edukasi seks tanpa terlihat jorok” itu, kita tahu betul godaan utama film semacam ini terletak pada bagaimana adegan sensual itu dieksekusi. Film ini punya dua versi, 17+ dan 21+ uncut. Oh, begitu. Jadi “edukasi” yang lebih “mendalam” cuma buat yang 21+ ke atas? Kayaknya ini bukan soal edukasi lagi deh, tapi lebih ke segmentasi pasar biar penonton bisa pilih “pendidikan” sesuai seleranya. Jangan-jangan, versi 21+ itu isinya cuma pelajaran anatomi yang lebih jelas, bukan filosofi Kamasutra Jawa yang mendalam.
Film ini adalah parade keberanian yang ‘malu-malu’, sebuah orkestra gestur dan tatapan yang dirangkai dengan alasan “edukasi budaya”. Penonton dipaksa buat ngapresiasi setiap adegan sensual yang katanya “puitis”, setiap bahasa Jawa yang “autentik”, karena katanya itulah “seni” yang ditawarkan. Tapi di balik semua visual yang bikin penasaran itu, jiwa edukasinya terasa berputar-putar di tempat, enggak berani masuk ke akar masalah. Seolah-olah, kalau filmnya sudah “menantang tabu”, penonton pasti lupa kalau pulang dari bioskop mereka enggak dapat apa-apa selain rasa ingin tahu yang belum terjawab. Gowok ini contoh nyatanya. Semua elemen teknisnya udah siap jadi “film drama budaya paling revolusioner,” tapi kalau pesannya cuma ngambang antara edukasi dan provokasi, ya jadinya kayak kelas anatomi yang disisipi kutipan Serat Centhini.
Ini lebih mirip demonstrasi bahwa Hanung Bramantyo “berani” bikin film sensitif, daripada sebuah karya yang komunikatif tentang esensi tradisi gowok itu sendiri. Ibaratnya, kayak dosen yang cuma bisa pamer materi kuliah yang rumit, tapi enggak tahu cara ngejelasin ke mahasiswanya biar paham. Ini bukan lagi soal filmnya jelek, tapi filmnya salah fokus dalam menyampaikan “ilmu”. Ambisi bikin karya yang jujur sama budaya dan seksualitas memang patut dipuji, tapi apa harus dengan mengorbankan kualitas jangkauan dan actionable insight kepada khalayak yang lebih luas? Kalau tujuannya cuma biar kita tahu ada tradisi gowok, kenapa enggak sekalian bikin buku sejarah aja? Lebih hemat, lebih “efektif” bikin sadar. Mungkin sutradaranya mikir penonton udah cukup pintar buat nyari filosofi sendiri setelah disuguhi tradisi ‘unik’ ini. Ya, niatnya bagus sih, tapi kan enggak semua orang ke bioskop buat belajar antropologi.
Sejarah yang ‘Nanggung’ dan Ambisi yang Terlalu Banyak
Film ini berlatar 1955-1965, sebuah era yang krusial dalam sejarah Indonesia. Ia mencoba mengangkat dekonstruksi patriarki, pendidikan seks, hingga kisah cinta segitiga (atau lebih?) yang dibumbui intrik politik. Wow, ambisinya luar biasa! Tapi, seringkali film yang terlalu ambisius kayak gini malah jadi “nanggung” di semua lini. Konflik cinta Ratri (Raihaanun) dan Kamanjaya (Reza Rahadian) yang terhalang status sosial dan dendam masa lalu, ditambah lagi intrik politik yang bikin kisah cinta jadi runyam. Ini film tentang pendidikan seks, drama percintaan, atau sejarah G30S? Kayaknya semua dimasukkin biar enggak ada yang protes kalau filmnya kurang komplit.
Kisah tentang perjuangan perempuan di era 60-an untuk menggapai mimpinya, yang katanya diwakili Ratri, juga sering terganggu oleh fokus pada adegan sensual atau konflik personal yang kurang matang. Film ini seolah ingin jadi manifesto feminis, tapi kok ya kebanyakan adegan intimnya yang terekspos? Mungkin memang itu strategi agar pesan feminisme-nya “lebih mudah masuk” ke kepala penonton. Bahkan ada karakter Liyan, anak angkat Nyai Santi yang feminin dan kemayu, yang katanya representasi “tabu” dalam tatanan Jawa. Oke, film ini memang berusaha inklusif dan progresif, tapi apakah itu perlu dicampuradukkan dengan elemen thriller dan intrik politik yang bikin cerita jadi makin pecah konsentrasi? Ini mau bikin penonton mikir atau cuma mau bikin kepala berasap?
Film ini gagal menyajikan detail yang cukup tentang bagaimana tradisi gowok ini berinteraksi dengan perubahan sosial dan politik pada masa itu, atau bagaimana “pendidikan seks” ini benar-benar memerdekakan perempuan di tengah patriarki yang masih kokoh. Fokusnya terlalu pada drama personal dan sensualitas yang “artistik”, hingga aspek konteks sejarah dan filosofisnya jadi tenggelam. Tampaknya para pembuat film terlalu sibuk mengejar buzz dan kemewahan visual, sampai lupa kalau film yang bagus itu butuh pondasi cerita yang kuat, bukan cuma tempelan isu-isu keren. Prioritas, kawan! Padahal, film yang kuat itu bukan cuma yang bisa bikin kita terbengong-bengong lihat adegan “berani”, tapi yang punya keberanian untuk ngasih tahu akar masalah patriarki atau bagaimana perempuan zaman itu berjuang. Ini mah, filmnya cuma kayak daftar panjang isu tanpa benang merah yang jelas, bikin kita cuma bisa garuk-garuk kepala.
Kesimpulan: Sensualitas yang Indah, tapi Pesan yang Kabur
Gowok: Kamasutra Jawa adalah film yang ambisius dan penting buat perfilman kita. Film ini sukses secara artistik dan nunjukkin kalau sinema Indonesia punya potensi besar untuk bikin film yang beda dari yang lain, dengan mengangkat isu sensitif dan budaya lokal. Tapi, ambisinya mau jadi karya seni yang jujur pada seksualitas dan feminisme malah jadi bumerang. Film ini mengorbankan kekuatan pesan dan aksesibilitas naratif demi bikin adegan-adegan yang puitis dan intim. Jadinya, penonton ngerasa ceritanya terlalu personal dan kurang punya daya dorong untuk mengubah pandangan. Mungkin tujuan utamanya memang bukan bikin film yang mengedukasi massa secara massal, tapi bikin mahakarya yang cuma bisa diapresiasi segelintir elite yang doyan seni tapi takut bicara vulgar. Strategi bisnis yang cerdas, tapi kurang “mengerti hati” rakyat.
Film ini adalah tontonan yang membuat kita merenung, tapi juga tantangan buat sineas Indonesia. Tantangan untuk enggak cuma mikirin adegan yang “seni banget” atau “berani”, tapi juga pastiin kalau setiap filmnya bisa berdiri sendiri sebagai karya seni yang utuh. Dengan karakter yang kuat dan tema yang digali dalam-dalam. Gowok: Kamasutra Jawa sudah membuktikan bahwa kita bisa membuat film yang menyentuh jiwa dan berani. Sekarang, yang dibutuhkan adalah cerita yang lebih kokoh dan punya keberanian untuk berbicara jelas, supaya film Indonesia enggak cuma keren di festival, tapi juga bisa nyentuh hati penonton tanpa harus sibuk menerjemahkan setiap simbol dan keheningan, atau bertanya-tanya, “Ini film apa sih? Kenapa cuma pamer paha tapi bilangnya edukasi?” Ya, kalau cuma adu sensualitas dan intrik, mending nonton drama Korea saja, gratis! Dan kalau cuma mau belajar sejarah, mending baca buku, tanpa perlu bayar tiket bioskop. Jangan sampai seni jadi alasan untuk malas menyampaikan pesan yang jelas. Karena, pada akhirnya, film yang bagus adalah yang bisa menyampaikan ceritanya dan mungkin, sedikit menggerakkan penonton untuk berbuat sesuatu, bukan sekadar memamerkan kemampuannya bikin penonton bengong dan galau. Bukankah begitu?